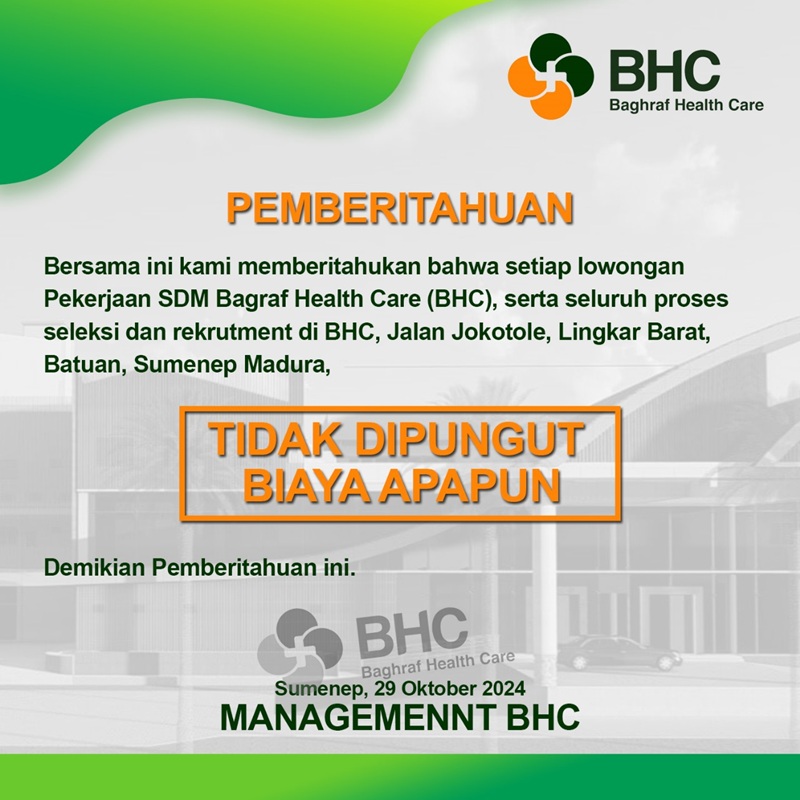Oleh: H. Darmadi*
Tahun 2014 pemerintah kembali membuka penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Dibukanya penerimaan Calon pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2014 menjadi angin segar bagi para pencari kerja (sarjana). Dan, dari tahun ke tahun, setiap ada penerimaan CPNS, animo masyarakat untuk mengikuti tes sangat tinggi. Mengapa harus jadi PNS? Lalu kemanakah belasan ribu yang tidak lolos seleksi PNS? Menganggur?.
Sekurang-kurangnya ada tiga motivasi mendasar, mengapa para sarjana ramai-ramai berburu profesi PNS. Pertama, soal status sosial. Ada anggapan yang berkembang bahwa profesi PNS dinilai masih memiliki strata sosial yang lebih tinggi di tengah masyarakat dibandingkan dengan profesi lain seperti petani, nelayan, atau wiraswata lainnya. Kedua, beban kerja yang sedikit. Masa kerja PNS rata-rata hanya lima hari (Senin-Jumat) dengan 7 – 7,5 jam per hari. Itu pun masih banyak waktu kosongnya. Kesibukan hanya terjadi di saat turunnya program kerja dari satuan/unit kerja terkait. Makanya, banyak PNS keluyuran di jam kantor atau bermain game di komputer kantor. Ketiga, gaji besar dan tunjangan masa depan yang pasti. Inilah motivasi terbesar, mengapa orang berlomba-lomba menjadi PNS.
Patut diakui bahwa selain tiga motivasi di atas, satu persoalan mendasar yang tak bisa dipungkiri adalah belum terbukanya lapangan kerja di sektor swasta yang menyerap banyak tenaga kerja. Investasi di Indonesia masih terbilang lemah. Belum banyak investor yang berani membuka lapangan kerja yang meyerap ribuan tenaga kerja. Padahal, potensi pertanian, kelautan, kehutanan dan pertambangan di Indonesia sebagian besar belum terjamah. Kendati demikian, kondisi ini tak bisa menjadi kambing hitam bagi seorang sarjana yang menganggur setelah tak lolos seleksi PNS. Bukankah seorang sarjana yang dicetak oleh perguruan tinggi dituntut untuk mampu menciptakan lapangan kerjanya sendiri? Dengan kata lain, perguruan tinggi harus bertanggung jawab atas mutu output yang dihasilkannya dan sedapat mungkin membenahi diri.
Perguruan tinggi di Indonesia akhir-akhir ini memang mendapat sorotan besar berkaitan dengan anjloknya mutu output yang dihasilkannya. Bahkan, sejumlah universitas besar ternama dan bermutu semisal UGM Yogyakarta dan ITB Bandung pun tak luput dari sorotan pemerhati pendidikan. Kualitas kemampuan, keahlian (skill), dan integritas moral-intelektual para sarjana dalam mengimplementasikan kesarjanaannya di tengah lingkungan kerja dinilai semakin menurun. Angka pengangguran membengkak karena mahasiswa tidak mampu dan tidak dipersiapkan untuk menciptakan lapangan kerja sendiri. Para lulusan yang tengah bekerja pun hanyalah menjadi kelompok pengangguran terselubung karena kualitas kerja yang ditunjukkan tidak sejalan dengan kompetensi yang dimilikinya. Menurut Engkoswara (1986:53), ada tiga (3) arus utama (main stream) yang menggejala dalam dunia perguruan tinggi. Pertama, menurunnya prestasi akademik mahasiswa. Penurunan prestasi akademik dimaksud tidak saja diukur dengan akumulasi indeks prestasi (IP) tetapi melingkupi juga daya produktif karya-karya individual mahasiswa. Gejala dan isu penting yang tengah merebak dalam dunia kampus adalah praktek jual-beli skripsi sebagai prasyarat meraih sarjana, jual beli gelar sarjana, pemalsuan gelar, dan mental belajar santai dan sok pintar. Disinyalir, trend hidup yang tengah mengancam mahasiswa ini dipicu oleh arus perkembangan teknologi yang pesat. Sebut saja maraknya penggunaan telepon seluler (handphone), facebook, internet dan konsumsi acara-acara televisi berlebihan yang turut memandulkan kreativitas dan semangat untuk belajar.
Kedua, sistem pengajaran dalam lembaga pendidikan kita yang menerapkan pola indoktrinasi. Sebagaimana jenjang pendidikan SD hingga SMA, perguruan tinggi pun hingga kini masih mengadopsi pola pengajaran feodal dengan mendikte (indoktrinasi) lewat sistem kejar paket. Prinsip dasar yang dipakai dosen adalah “asal menebarkan informasi,” entah dimengerti atau tidak yang penting selesai menurut limit waktu per semester. Teknik pengajaran ini dalam bahasa tokoh pendidikan kontemporer Paulo Freire disebut sebagai banking system, di mana memori mahasiswa hanya menjadi bank pasif yang mendepositkan sejumlah materi pengajaran dari para dosen. Potensi intelegensia seperti daya analisisis, logika berpikir dan daya kritis mahasiswa tidak dimanfaatkan (Suparno, 2001:152). Ketiga, orientasi yang salah arah. Gejala paling tampak yang muncul dalam diri anak-anak lulusan SMA/SMK akhir-akhir ini, adalah berkuliah di fakultas-fakultas yang paling banyak dibutuhkan dalam formasi PNS. Akibatnya, seringkali mereka terjebak dalam pilihan kuliah yang pragmatis tanpa melihat kemampuan dan potensi yang cocok dalam dirinya, apalagi unsur ‘paksaan’ dari orang tua turut menyertainya. Sebut saja Akademi Perawatan (Akper) dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) yang sesak dengan ratusan mahasiswanya.
Nah, ketika kita berhadapan dengan ribuan orang yang ramai-ramai berburu PNS dengan formasi yang sangat sedikit, bagaimana perguruan tinggi dan para mahasiswa menyikapi ancaman pengangguran? Adalah tanggung jawab pihak penyelenggara pendidikan di setiap perguruan tinggi untuk merefleksi dan berbenah diri. Sebab sebagai jenjang pedidikan terakhir yang berinteraksi langsung dengan dunia kerja, setiap perguruan tinggi harus lebih terbuka dan proaktif untuk mengembangkan pola pendidikan yang tepat dan efektif demi menghasilkan lulusan yang bermutu, kreatif, dan kompeten di bidangnya. Pola pengajaran yang indoktrinatif harus diganti dengan meletakkan pengembangan daya intelegensi dan kreativitas sebagai aspek utama arah pendidikan. Pembukaan ruang gagasan lewat diskusi, seminar dan tulis menulis serta praktek kerja lapangan harus lebih banyak diberikan kepada mahasiswa.
Di sisi lain, tentunya upaya dan kerja keras mahasiswa untuk tetap mengembangkan diri melalui belajar secara otodidak guna mengasah kompetensi dan memperluas cakrawala pengetahuan dan keterampilan juga menjadi tuntutan dialogis. Sebab berhadapan dengan dunia kerja kelak, satu-satunya solusi yang bisa mengimbangi buramnya sistem pendidikan di perguruan tinggi adalah berani untuk mandiri dalam berpikir, berkreasi dan berinovasi. Dan ini hanya dapat dicapai dengan ketekunan belajar secara otodidak agar mahasiswa tidak terpasung dan mandul dalam legalitas gelar akademik semata-mata hanya pada jurusan yang dipilihnya. Sarjana bermutu adalah sarjana yang mampu menciptakan lapangan kerja sendiri dan siap menghadapi perubahan di luar tembok kampus. Dan tentunya perlu dukungan sepenuhnya dari instansi pemerintah terkait yang dalam hal ini telah ikut serta secara aktif dan terencana untuk menyiapkan lapangan-lapangan kerja seluas-luasnya, sehingga mampu menimbulkan minat bagi angkatan kerja baru untuk membuka usaha sendiri atau bekerja di sektor-sektor swasta daripada mengejar mimpi menjadi pegawai negeri.
*) Pegawai Fungsional Guru Kantor Kemenag Kab.Lampung Tengah, Dosen STKIP Kumala Lampung.