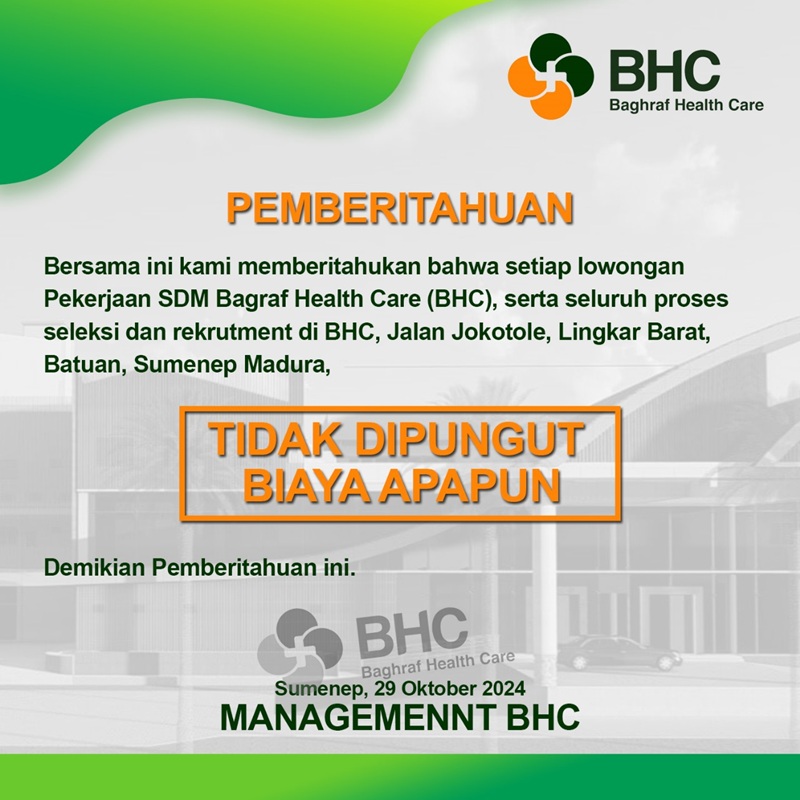Oleh : Rio F. Rachman*
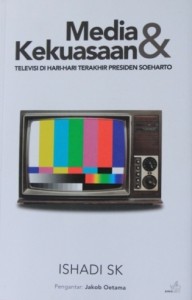
KARL Marx tidak sepenuhnya benar saat berasumsi bahwa media adalah kaki tangan kekuasaan kapitalis. Terbukti, awak media menjelang orde baru tumbang di Indonesia 1998 lalu, mengarahkan peluru-peluru kritis pada penguasa. Meskipun penguasa saat itu banyak yang merangkap sebagai pemilik modal perusahaan media.
Tak hanya people power yang bergelora. Pekerja media massa yang selama puluhan tahun jengah dipaksa “berseragam” turut menyisingkan lengan baju. Sulit menyebutkan mana yang lebih dulu memulai aksi. Apakah rakyat (akademisi, mahasiswa, dan tokoh masyarakat) atau media massa. Dalam teori gerakan sosial disampaikan, semua elemen yang memiliki tujuan sama, akan bersinergi dengan porsi dan caranya masing-masing.
Selain tentang teknis, sejarah, dan seluk beluk media televisi, Media & Kekuasaan mengupas gerakan-gerakan media massa menjelang reformasi atau runtuhnya orde baru era Soeharto. Khususnya yang terjadi di studio televisi. Buku yang merupakan desertasi Ishadi SK pada program doktor komunikasi massa Universitas Indonesia ini memiliki banyak kisah di balik layar. Disuguhkan dengan lugas dengan gaya bahasa ringan nan memikat.
Misalnya, saat RCTI mendapat wawancara eksklusif di gedung DPR beberapa hari sebelum Soeharto mundur. Isinya, Harmoko sebagai Ketua DPR/MPR meminta Soeharto mundur. Padahal, selama 15 tahun dia dikenal sebagai murid terbaik Presiden kedua RI tersebut. Bahkan pada 1 Maret 1998, palu sidang istimewa sampai patah karena Harmoko terlalu bersemangat mengetukkannya untuk mengesahkan Soeharto jadi presiden kali ketujuh.
Rilis ini merupakan berita menarik dan paling ditunggu. Tapi di sisi lain, potensial membuat berang keluarga Cendana. Apalagi, waktu itu RCTI dikuasai oleh Bambang Trihatmojo. Setelah melalui perdebatan panjang di ruang redaksi, akhirnya Desi Anwar membacakan berita itu dalam news break pukul 17.00. Benar saja, dua menit kemudian, Alex Kumara menerima telepon dari kediaman Bambang Tri (halaman 90).
“Selalu ada tarik menarik antara dua kepentingan dalam jurnalistik. Kepentingan bisnis owner dan kepentingan idealisme,” kata Ishadi dalam peluncuran Media & Kekuasaan di Universitas Airlangga, Surabaya, Maret lalu.
Selain RCTI, sempat disinggung pula wawancara Ira Koesno dan Sarwono Kusumaatmaja dalam sesi interaktif di Liputan 6 SCTV. Dalam kesempatan itu, Sarwono menyebutkan, negara dalam kondisi seperti orang sakit gigi. Solusinya, gigi yang sakit harus dicabut. Sejumlah elemen intelejen berasumsi, apa yang dikatakan Sarwono adalah kode agar mahasiswa menduduki istana.
Tak ayal, ini mengundang reaksi penguasa yang lantas mengontak kru di studio saat itu juga. Semua produser diminta meninggalkan tempat dan program dihentikan di tengah jalan. Hanya tinggal Ira Koesno dan seorang program director di sana. Mereka kemudian segera menutup acara dengan perasaan bingung. Sejak saat itu, sesi interaktif ditiadakan (halaman 104).
Perlawanan media tidak hanya dipandang melalui keberanian dengan penguasa. Namun juga keberanian untuk independen dari segala intervensi. Semisal saat Fokus Indosiar pada 21 Mei 1988 pagi menayangkan berita bahwa Soeharto ingin lengser di hari itu.
Padahal malam sebelumnya Amien Rais mewanti-wanti wartawan untuk tidak menayangkan itu. Tokoh reformasi itu kuatir, kabar tersebut kontraproduktif. Indosiar bergeming dan tidak terjadi apa-apa. Indosiar pun menjadi media yang terdepan dan terakurat, dalam menyuguhkan informasi waktu itu. Sebuah predikat yang selalu diidam-idamkan semua media.
Media, termasuk televisi, bukan seperti Ekalaya dalam kisah Mahabharata. Seorang pemanah yang terlalu patuh pada guru Drona sampai rela kehilangan jempol kanan hingga tumpaslah kehebatan memanahnya.
Dalam negara demokrasi yang sehat, media tidak harus tunduk pada pemerintah. Media dan demokrasi tidak bisa dipisahkan. Mereka seperti dua tubuh, satu jiwa. Demokrasi tanpa media akan mati. Media tanpa demokrasi pasti terbungkam.
Berproses Menguat
Ada sedikit kesamaan antara 1998 dengan 2014. Keduanya sama-sama tahun politik. Meski jelas pula perbedaannya. Pada 1998, terlihat keberanian media yang lama ditekan dan dipaksa “berseragam”. Sedangkan tahun ini, media massa, utamanya televisi, sudah diplot oleh banyak pemegang kapital yang juga politisi.
Terdapat pula perbedaan atmosfer politik antara dulu dan sekarang. Jika pada tahun 1998, semua media dan bahkan elemen masyarakat, memilih bersatu dengan tujuan tunggal: meruntuhkan pemerintahan otoriterian. Saat ini, media terpecah. Saling jegal.
Lalu bagaimana masa depan media di Indonesia yang dikuasai para politisi dan pemburu jabatan yang suka main jegal dalam pemberitaan? Tenang saja, kondisi ini adalah proses penguatan menuju media yang representatif.
Negara maju sekelas Jepang dan Amerika Serikat pun butuh waktu yang panjang untuk membentuk media yang proporsional. Seperti halnya televisi yang butuh waktu nyaris dua ratus tahun –sejak era pencetusan komunikasi elektromagnetik Faraday-untuk bertransformasi dari sebentuk tabung antik menjadi LCD tipis.
Saat buku dan literatur tentang media digelontorkan di kampus dan ruang publik lainnya. Tatkala orang-orang yang paham soal propaganda media massa terus membagi wawasannya pada sebanyak-banyaknya orang. Sewaktu itulah secercah harapan timbul dan terus mengembang. Masyarakat makin dirangsang kritis dan sedikit demi sedikit melupakan media pragmatis. Mau tak mau, media akhirnya “mengalah” pada masyarakat. Lalu, menjalankan fungsinya sebagai representasi masyarakat. (*)
*) Penulis adalah penerima beasiswa LPDP, Mahasiswa S2 Media dan Komunikasi Universitas Airlangga Surabaya.