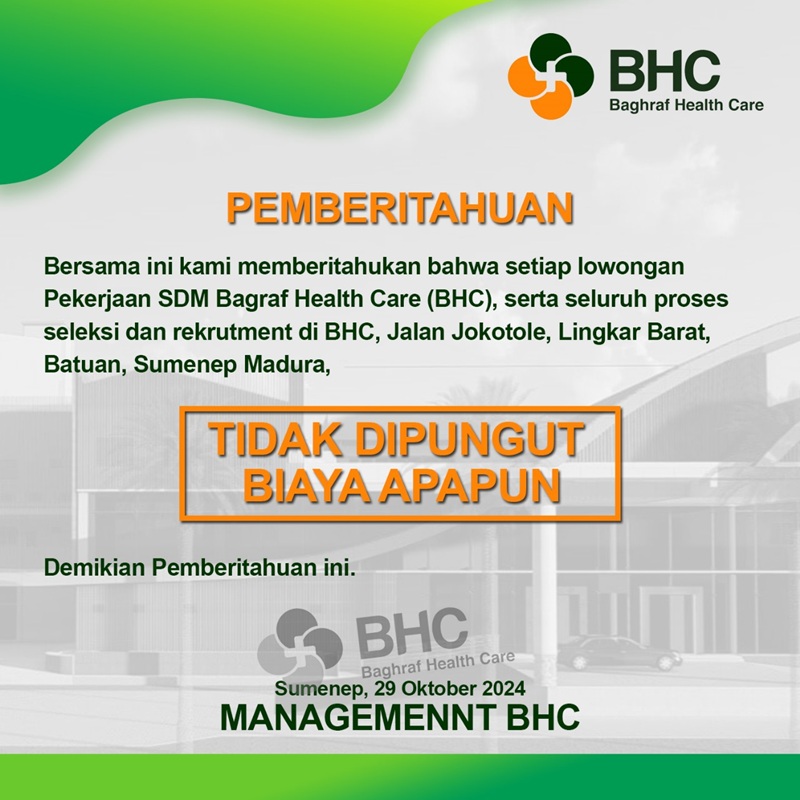Oleh: Muhammad Itsbatun Najih*
Wisata bencana adalah nomenklatur paradoksal. Juga tersebut Oksimoron: majas yang menempatkan dua antonim dalam suatu hubungan sintaksis. Wisata mengandaikan plesiran bersenang-senang melepas penat. Sedangkan bencana diartikan dengan elegi, nestapa, dan tidak diharap kedatangannya.
Keeksotikan alam Nusantara menjajakan ribuan destinasi wisata. Jejak peradaban masa silam dan parade gunung berapi menjadi wahana menarik turis manca maupun lokal. Modal alam yang demikian itu telah dikelola guna sebagai stimulus ekonomi dan pengembangan budaya. Sektor pariwisata berbasis alam eksentrik dapat menambah pundi-pundi kas pemerintah daerah dan geliat kesejahteraan masyarakat setempat dengan jualan cendera mata, kuliner, dan jasa pemandu.
Sayangnya, iklim pariwisata Tanah Air tidak selalu berkabar baik. Semisal terjadi bencana alam. Praktis tingkat kunjungan turis mendadak turun drastis yang berakibat terancamnya sektor pariwisata (ekonomi). Namun, di sisi lain bencana nyatanya membawa “berkah”. Justru, ketika bencana mengakibatkan tangis pilu dan hancur leburnya harta benda bahkan nyawa, sekonyong-konyong menarik naluri dan empati masyarakat luas; di samping untuk membantu korban bencana, juga tertambat hasrat keingintahuan seputar bencana itu sendiri berikut aspek turunannya (baca: kultur).
Dalam jangka panjang, suatu efek bencana bila dikelola optimal akan menghasilkan laba ekonomi maupun pengetahuan (mitigasi) –keadaban menghadapi alam. Yogyakarta telah menempuh jalur demikian. Pascaerupsi Gunung Merapi pada 2010, banyak masyarakat yang secara langsung ingin menyaksikan kedahsyatan terjangan wedhus gembel (awan panas). Banyak puing bangunan, bongkahan batu, dan jejak vegetasi yang terbakar sengaja dibiarkan sebagai “komoditas jualan” terhasrat sebagai wisata.
Kini berdiri pula Museum Gunung Merapi (MGM) dengan harapan pengunjung museum bisa melek perihal Gunung Merapi beserta seluk beluknya. Hal semacam ini bisa menjadi referensi dalam upaya pengurangan risiko bencana yang dikemas secara komersial. Bahkan area Lumpur Sidoarjo sudah jauh-jauh hari dijadikan rujukan baru destinasi wisatawan lokal. Sebagian masyarakat setempat menarik iuran masuk, menawarkan jasa ojek keliling area lumpur, dan berjual keping VCD bencana lumpur.
MGM juga bisa dijadikan tamsil perihal edukasi kebencanaan dan pusat riset. Jadi, pemaksimalan orientasi atas stigma Merapi, Sinabung, maupun Tsunami Aceh tidak sebatas pada imaji kengerian. Melainkan pada perimbangan dengan asosiasi wisata dan pemunculan kesadaran bertangguh bencana. Pemaknaan berwisata bencana tidak sama sekali diartikan ketika terjadi bencana masyarakat berduyun-duyun mendatangi lokasi sebagai ajang tontonan. Anggapan ini rupanya masih berlaku di benak sebagian masyarakat sehingga wisata bencana menghasilkan pro-kontra dan sinisme. Berwisata bencana lantas diartikan sebagai laku tidak etis.
Padahal, wisata bencana terkira menjadi saluran hilir dari proses tanggap bencana pascaproses pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Artinya, setelah masyarakat tertimpa bencana dan telah mampu melakoni hidup normal lagi, barulah kemudian merancang sebuah (efek) bencana untuk dikelola (dikomersialisasikan). Etiskah sebuah bencana dijadikan ajang cari peruntungan materialistik? Pembuatan objek wisata bencana di samping mengedukasi masyarakat atas sebuah bencana, juga terharap laku kontemplasi para turis, serta menyibakkan bukti bahwa masyarakat terdampak bencana bisa bangkit dari keterpurukan.
Di luar negeri, wisata bencana bukan barang baru. Pascagempa bumi dan tsunami pada 2011, bermunculan tempat wisata bencana di Jepang. Amerika Serikat menjadikan daerah New Orleans yang pernah dilanda badai Katrina sebagai objek wisata. Beberapa area sengaja dibiarkan tidak perbaiki guna kepentingan pariwisata. Pun Ukraina menyediakan tur exclusion zone di Chernobyl yang pernah dilanda ledakan nuklir. Bahkan UNESCO menetapkan situs Auschwitz –kamp pembantaian Nazi– sebagai tempat wisata. Pula Ground Zero yang ramai didatangi turis sebagai napak tilas tragedi WTC.
Pemerintah ataupun swasta dapat mengambil bagian dari pengembangan wisata bencana dengan menyiapkan kelengkapan infrastruktur untuk dijadikan destinasi wisata alternatif. Bisa pula sekaligus dijadikan pusat studi/kajian kebencanaan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Marie Elka Pangestu pernah berencana menjadikan para korban bencana erupsi Gunung Sinabung dan Kelud sebagai pemandu wisata dan perajin. Menurut Marie, masyarakat biasanya banyak datang ke sekitar daerah bencana untuk melihat-lihat. Hal itu dapat dimanfaatkan untuk menjajakan produk kerajinan maupun kuliner (Merdeka.com 19/02/2014).
Terma bencana merujuk pada Undang-undang No. 24 Tahun 2007 adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Sementara menurut Faulkner (2001) bencana adalah bencana alam, sedangkan bencana non-alam dan sosial disebut sebagai krisis. Namun terlepas dari pemaknaan bencana, cakupan wisata bencana kiranya tidak sekadar berasosiasi pada terdampak tanah longsor, erupsi gunung, gempa bumi, atau tsunami. Tapi juga yang tersebab oleh murni laku manusia atau disebut oleh antropolog Bohannan sebagai bencana sosial.
Langkah inspiratif dilakukan oleh biro pariwisata Filipina; menawarkan paket wisata bencana yang mewajibkan para turis ikut serta melakukan upaya rekonstruksi objek wisata Filipina yang telah luluh lantak oleh badai Haiyan pada akhir 2013. Maka, benar kata DeMond Shondell Miller (2008) bahwa wisata bencana membuka kesempatan untuk merasakan kesusahan yang diderita orang lain. Lebih lanjut, wisata bencana memberi seruan moral untuk arif pada alam serta stimulus edukasi perihal mitigasi bencana. Walhasil, wisata bencana hakikatnya bukan “plesiran” nirmakna, melainkan berorientasi penghayatan atas kemanusiaan dan etos menghargai alam.
*) Pemerhati Sosial