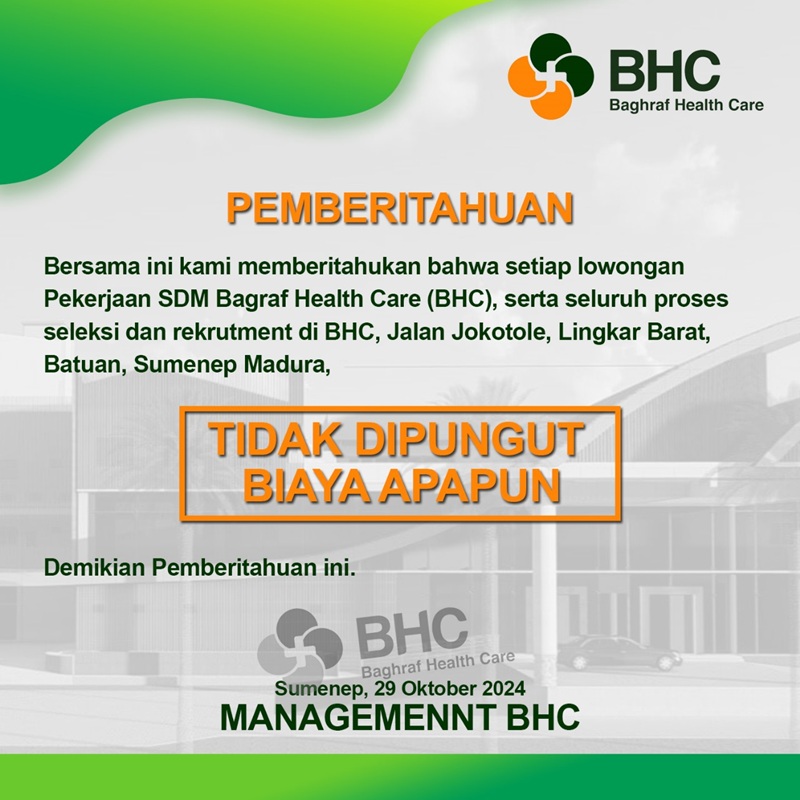Oleh: Muhammad Najib*
Penetapan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik sebagai tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinyatakan telah melakukan praktik pemerasan dan penyalahgunaan wewenang menambah daftar panjang kasus korupsi yang menjerat pejabat tinggi negara. Kasus ini sekaligus memperjelas bahwa indikasi bahwa korupsi telah menjamur di seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kasus tersebut juga menjadi pil pahit yang harus ditelan oleh Kabinet Indonesia Bersatu II. Jero bukanlah orang pertama yang terjerat korupsi kaitannya dengan menteri yang aktif di kabinet yang terjerat korupsi. Jelasnya, Jero menyusul dua rekannya, Surya Dharma Ali (Menteri Agama) dan Andi Mallarangeng ( Menteri Pemuda dan Olahraga).
Keadaan ini, oleh Presiden SBY dijadikan dalih bahwa era pemerintahannya adalah era memerangi korupsi dengan tidak pandang bulu. Terbukti, SBY dengan segala otoritasnya bisa saja melindungi menteri-menterinya dari jeratan hukum kasus korupsi. Tapi, dengan terungkapnya tiga menteri sebagai tersangka, mencerminkan bahwa “tidak ada halangan” bagi KPK untuk menjerat tersangka korupsi di ranah kekuasaan SBY.
Agaknya, ini bisa jadi hanya alasan yang tak dapat dijadikan patokan bahwa korupsi sudah dapat dibumi hanguskan. Bahkan, fenomena tersebut, bagi masyarakat bisa dimaknai bahwa “tidak ada” pejabat di negeri ini yang tidak korupsi. Hal ini didasarkan bahwa atasannya saja kerap melakukan praktik korupsi. Bagaimana kondisi bawahannya. Mustahil jika korupsi dilakukan secara pribadi tanpa melibatkan orang lain atau kelompok tertentu. Inilah yang kemudian muncul istilah mata rantai korupsi.
Fokus Pemberantasan Korupsi
Di Indonesia, orang korupsi masih dianggap “suci”. Hal ini terbukti, ketika dalam pelantikan DPR kemarin, orang yang sudah jelas terjerat korupsi masih dilantik sebagai wakil rakyat. Fenomena ini menjadi ankedot. Bagaimana tidak, masyarakat sudah tidak jeli dalam menentukan pemimpinnya. Terlepas dari faktor penyebabnya, fenomena tersebut sungguh memalukan ditengah perang terhadap korupsi ditabuh kencang.
Setidaknya ada dua hikmah atas penetapan Jero Wacik sebagai tersangka. Pertama, lingkaran kekuasaan masih menjadi bulan-bulanan praktik korupsi. Dan lingkaran inilah yang seharusnya menjadi fokus pemberantasan korupsi. Artinya, pemberantasan korupsi harus segera ditabuh dan dimulai dari “jeroan” korupsi, yakni lingkaran lingakaran dalam pusat kekuasaan.
Kedua, sektor minyak dan gas adalah sektor yang harus gencar dikuak dan dibongkar. Tahun lalu, KPK berhasil menguak korupsi kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu (SKK) migas Rubi Rubiandini. Perlu diketahui bahwa sektor ini merupakan sektor penyumbang APBN dengan besaran ratusan triliun rupiah setiap tahun. Konkretnya, konribusi ke APBN mencapai 320 triliun rupiah setiap tahun. Dan disektor inilah uang negara bocor atau madek dikantong pribadi. Melihat praktik korupsi di sektor minyak dan gas bumi begitu massif, sudah sepatutnya KPK gencar menguak dan menyelamatkan uang negara supaya rakyat dapat meraskan manisnya keadilan dan kesejahteraan.
Gencarnya KPK menagkap koruptor idealnya diimbangi dengan sinergi sesama penegak hukum. Artinya, usaha “mati-matian” KPK harus dibarengi dengan putusan hukuman berat terhadap perilaku kejahatan sosial oleh penegak hukum, Hakim tindak pidana korupsi (tipikor), misalkan. Sebab, fenomena yang seringkali terjadi dilapangan antara tuntutan Jaksa KPK tidak berbanding lurus dengan putusan Hakim Tipikor. Kebanyakan, putusan Hakim Tipikor lebih rendah dari tuntutan jaksa KPK.
Kasus sama terjadi pada Ratu Atut Chosiyah. Vonis yang dijatuhkan hakim tipikor terhadap terdakwa Ratu Atut menuai banyak kecaman. Putusan itu dinilai tidak sepadan terhadap dosa yang telah dilakukan dan cenderung menimbulkan pesimistis pemberantasan korupsi. Sebelumnya, jaksa KPK menuntut Ratu Atut Chosiyah hukuman 10 tahun dan denda sebesar Rp 25o juta. Akan tetapi, hakim tipikor berkehendak berbeda, yakni memutuskan hukuman bagi Atut empat tahun dan denda sebesar 200 juta subside kurungan lima bulan. Atut dikenai pasal 6 ayat 1 huruf a atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Negeri ini akan menjadi negeri maju, sejahtera, dan bermartabat manakala negeri ini bebas korupsi. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan sinergi oleh semua eleman masyarakat. Dan tak kalah pentingnya juga kinerja lembaga “super body” seperti KPK. Simpelnya, kinerja KPK harus mendapatkan dukungan dari hakim tindak pidana korupsi. Manifestasi dukungan tersebut dalam bentuk penjatuhan hukuma seberat-beratnya. Gencar menerapkan UU pencucian uang dalam setiap kasus korupsi merukan keharusan. Kekayaan negara yang dijarah koruptor harus dikembalikan pada haknya.
Jika upaya memiskinkan koruptor gencar dilakukan atau diterapkan, maka akan berdampak mencegah berulangnya praktik penjarahan uang negara. Bahkan, kalau perlu hukuman seumur hidup juga harus tetap “dibumikan”. Hal ini sebagai langkah menuju negeri bebas korupsi. Bebas dari praktik korupsi adalah langkah menuju hakikat kemerdekaan, yakni terwujudnya kesjehteraan dan keadilan sosial. Hakikat kemerdekaan tersebut akan menghantarkan manusia pada optimalnya harkat kemanusiaan. Mustahil harkat kemanusiaan dapat optimal jika korupsi masih menghiasi negeri.
Oleh sebab itu, menjadikan pemberantasan korupsi sebagai musuh bersama harus benar-benar ditegakkan. Keberanian dan ketangkasan KPK untuk menguak kasus korupsi serta hukuman berat dari hakim tipikor bisa menjadi awal kepunahan praktik korupsi di negeri ini. Memang, ketegasan dan “ketegaan” pemerintah adalah modal awal membumi hanguskan korupsi. Dan yang demikian itu sejatinya telah dipraktikkan lebih dulu oleh negara China. “kegegaan” dapat dilihat ketika ada orang terbukti korupsi dengan skala besar, maka hukuman yang diberikan adalah hukuam mati. Pertanyaannya, kapan Indonesia bisa seperti itu dalam memperlakukan koruptor kelas kakap? Wallahu a’lam bi al-Shawab.
*) Ketua Kajian Ilmu Kalam Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang, Peneliti Muda di Monash Institute Semarang