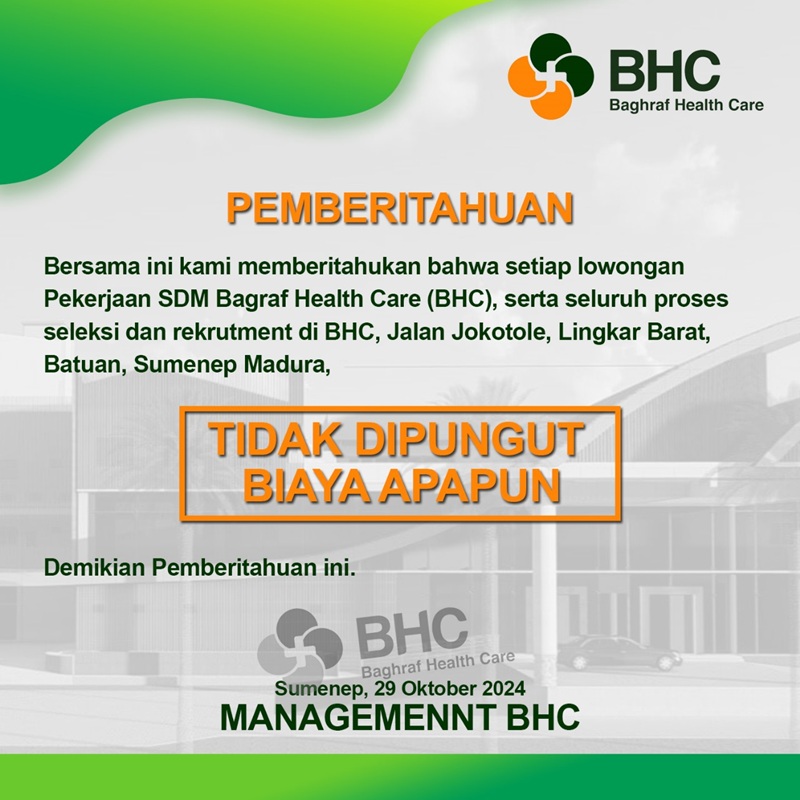Oleh: Darmadi*
Bencana alam kini menjadi rutinitas dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dua musim yang ada memiliki katastrofanya masing-masing. Musim panas kerap menda-tangkan kekeringan dan kebakaran hutan. Sedangkan musim hujan hampir selalu membawa banjir dan tanah longsor. Di belahan bumi lain, peningkatan tajam suhu udara, badai, serta bencana lain juga tak kalah mengancam.
Bencana alam kini menjadi rutinitas dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dua musim yang ada memiliki katastrofanya masing-masing. Musim panas kerap menda-tangkan kekeringan dan kebakaran hutan. Sedangkan musim hujan hampir selalu membawa banjir dan tanah longsor. Di belahan bumi lain, peningkatan tajam suhu udara, badai, serta bencana lain juga tak kalah mengancam.
Bencana-bencana semacam itu bisa saja merupakan fenomena alam tanpa campur tangan manusia. Namun bila ditelusuri tampaknya manusia jauh lebih memiliki andil pada terjadinya bencana tersebut dibandingkan dengan alam itu sendiri. Alam selalu bekerja dalam keserasian. Alam adalah sistem, dan layaknya sebuah sistem alam berjalan dalam keseimbangan , keteraturan dan kesatuan (totalitas).
Ada persepsi dan pola interaksi yang salah dari manusia terhadap alam. Kita tidak memiliki kesadaran ekologis, yaitu kesadaran akan eksistensi kita, manusia, sebagai subsistem alam yang harus selalu berada dalam sistematikanya (alam). Atas nama pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, keamanan atau bahkan ilmu pengetahuan kita sering kali dengan jumawa memperlakukan alam sebagai entitas yang harus ditaklukkan. Seolah alam merupakan sumber daya tanpa batas yang diperuntukkan bagi manusia belaka. Lebih tepatnya bagi manusia saat ini, bukan bagi manusia-manusia yang akan datang.
Persoalan sikap mental eks-ploitatif manusia sebenarnya telah lama mengemuka Sejak awal abad kedua puluh, masalah lingkungan sudah menjadi bagian dari isu penting dalam kancah global. Ratusan lembaga yang hirau akan lingkungan sudah berjumlah ratusan. John Baylis dan Steve Smith dalam The Globalization of World Politics (2005) mencatat, pada tahun 2000 saja terdapat lebih dari 300 perjanjian multilateral tentang lingkungan dan pada tingkat bilateral jumlahnya jauh lebih banyak lagi.
Benarkah manusia telah menemukan puncak kesadaran ekologisnya? Kemapanan telah membelalakkan sensitivitas ekologis sebagian kecil manusia. Dirinya sadar akan eksistensi-nya yang merupakan sub-sistem dari kosmos. Itupun muncul sebagai respon atas gejala-gejala ketimpangan kosmis (bencana) yang sering terjadi, bukan murni kesadaran preventif. Namun begitu mereka menjadi perintis upaya mereduksi apa yang disebut Garrett Hardin (1968) sebagai tragedy of the commons, yaitu tindakan-tindakan rasional individu yang mengarah pada berbagai perilaku kolektif yang mengakibatkan eks-ploitasi berlebih terhadap sumber daya alam sehingga me-ngakibatkan bencana.
Hardin berargumen bahwa ketika akses terhadap sumber daya alam terbuka lebar dan tidak ada aturan yang mengikat, manusia akan terus-menerus mengeksploitasinya sampai pada batas maksimal demi kepentingan pribadinya. Masing-masing akan memperoleh keuntungan maksimal dari penggalian sumber daya alam tersebut. Akan tetapi, akibat-akibat logis dari over-eksploitasi yang berupa bencana alam tentunya akan ditanggung bersama. Sayangnya, manusia-manusia semacam ini senyatanya masih merupakan mayoritas. Inilah yang menjadi persoalan serius umat manusia.
Dalam konteks ini, menawarkan gagasan filosofis tentang bagaimana kita harus be-rinteraksi dengan alam adalah hal yang patut dipertimbangkan. Dampaknya mungkin tidak bersifat instan, namun upaya ini tetap penting guna menumbuhkan kesadaran kolektif akan urgensi agenda-agenda penyelamatan ekologi demi kelestariannya dan tentunya demi kelastarian kehidupan manusia sendiri.
Pada awal abad ke-19, Alferd North Whitehead merintis apa yang disebut sebagai filsafat organisme. Whitehead mencoba merevitalisasi tradisi ontologi yang dianggapnya sedang me-ngalami masa-masa keruntuhan akibat terjangan gelombang keilmuan modern yang bertumpu pada nilai-nilai materialisme positivistik.
Paradigma materialisme positivistik inilah yang melahirkan mental eksploitatif atas alam semesta. Paradigma semacam ini memandang semesta sebagai entitas materi yang rigid sehingga harus difungsikan secara kalkulatif. Maka sebagai respon terhadap paradima sains mo-dern tersebut, Whitehead dalam Process and Reality (1978) menawarkan filsafat organismenya yang mengedepankan keutuhan dan integrasi di antara jejaring realitas dalam bingkai pemikiran sistemik.
Setiap entitas di jagad raya memiliki nilai-nilai intrinsik masing-masing, tak terkecuali manusia. Eksistensi manusia hanyalah bagian kecil dari entitas-entitas sistemik jagad raya yang bermiliar-miliar bahkan trilyun. Tidak sepantasnya manusia “mengklaim” diri sebagai supremasi atau bahkan pusat alam semesta sehingga dengan tanpa kendali mengeksploitasinya. Bila demikian, maka hakekatnya manusia menggilas dirinya sendiri dalam rajutan semesta yang maha luas.
Pengandaian ontologis tersebut merupakan landasan untuk membangun sebuah moralitas baru. Kita (manusia) adalah kesatuan yang komplementer dengan triliunan kesatuan-kesatuan lain dalam semesta. Penciptaan dan eksistensi manusia terkait erat dengan penciptaan dan eksistensi binatang, tumbuhan, tanah, air, udara dan unsur-unsur alam lain. Manusia sama sekali bukan diri yang terpisah dari diri-diri di alam semesta. Alam bekeja dalam keteraturan dan keseimbangan, maka kesatuan-kesatuan ini harus secara normal berjalan pada jalur dan fungsinya masing-masing.
Internasilasi posisi manusia sebagai sub-sistem alam semesta diharapkan akan mampu membangkitkan kesadaran kritis untuk bersedia merekons-truksi setiap klaim superioritas atas alam. Ketika manusia mampu melewati tahapan kesadaran kerdil tersebut dan menggantinya dengan cara pandang yang utuh dan jujur atas realitas ekologis, maka bagi Whitehead dia berarti telah berevolusi menjadi sebuah ”diri ekologis”. Yaitu “diri” yang mempunyai tanggung jawab untuk melestarikan dan menciptakan keselarasan hubungan dengan satuan-satuan aktual lainnya, yang sadar bahwa koeksistensinya dengan alam adalah niscaya demi keberlangsungan dirinya dan generasi-generasi berikutnya. Lebih dari itu, dia adalah sebagai wujud pengakuan diri atas supremasi Pencipta Yang Maha Agung. [*]
*) Praktisi pendidikan, pemerhati masalah sosial, budaya, dan politik. Tinggal di Lampung Tengah.