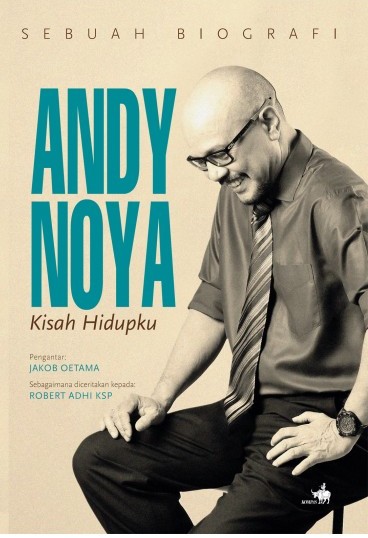Maling berpesta di kampung Budi. Dalam sepuluh hari terakhir ini, empat warga kampung Budi kehilangan sepeda, televisi, kelinci, ayam, selimut di jemuran, dan barang sederhana lainnya.
Maling berpesta di kampung Budi. Dalam sepuluh hari terakhir ini, empat warga kampung Budi kehilangan sepeda, televisi, kelinci, ayam, selimut di jemuran, dan barang sederhana lainnya.
Kampung Budi dibelah jalan beraspal kelas III yang menghubungkannya dengan kampung lain. Rumah-rumah di utara jalan berhimpitan, berdesak-desakan mirip daerah kumuh di kota.
Di selatan jalan hanya ada lima rumah yang jarak antar rumah agak berjauhan. Empat dari lima rumah itulah yang kemalingan dalam sepuluh hari terakhir ini. Di belakang lima rumah selatan jalan itu terdapat kuburan, kebun, sawah, sungai, dan hutan kecil. Orang-orang yakin, ke sanalah maling itu melarikan diri.
“Maling itu pasti orang miskin. Melihat apa saja yang dibawa kabur maling itu, jelas bukan perbuatan orang kaya,” kata isteri Budi, suatu malam, di ranjang besi mereka.
Istri Budi menatap langit-langit kelambu biru. Selimut putih bergaris-garis biru membungkus tubuhnya. Perutnya tampak membuncit.
“Kau sedang hamil muda, tak baik bicara tentang maling. Nanti anak kita….”
“Bagaimana menurutmu?” isteri Budi memiringkan tubuh ke kiri, menatap Budi. “Maling itu pasti orang miskin, bukan?”
“Yeah,” Budi bergumam. “Maling itu orang miskin.”
“Karena orang kaya tidak mengambil ayam atau selimut di jemuran. Orang kaya mencuri anggaran proyek.”
“Apa mandor proyek sepertiku bisa menjadi maling?”
Isteri Budi tersenyum.
“Kau tidak. Kau mandor yang baik. Aku percaya itu.”
“Terima kasih. Kau pun isteri yang baik. Aku percaya itu.”
Isteri Budi mengubah posisi tubuhnya. Sekarang ia telentang dan memandang langit-langit kelambu biru. Ia menyebut lima warga kampung yang layak dicurigai sebagai maling.
Budi terhenyak.
“Mengapa kau masukkan juga Pak RT sebagai tersangka?”
Isteri Budi menoleh.
“Tidakkah kau curiga, sebentar lagi Pak RT punya gawe, menikahkan anak perempuannya. Dari mana seorang buruh tani macam Pak RT punya uang untuk menikahkan anaknya, bila bukan dari mencuri? Kau tentu sudah dengar, Pak RT akan menanggap organ tunggal. Dari mana ia punya uang?”
“Mungkin calon besannnya yang menyewa organ tunggal?”
“Calon besannnya pun buruh tani. Calon menantunya lebih parah, pekerjaannya tak menentu. Mereka orang-orang tak punya uang.”
“Kau jangan berburuk sangka. Tak baik untuk janinmu…”
“Ini analisis, bukan buruk sangka.”
“Kalau Pak RT seburuk analisismu, mengapa ia bisa menjadi ketua RT?”
“Karena ini kampung kerajaan.”
“Maksud kau?”
Isteri Budi mendesah.
“Aku lupa, kau baru setahun di kampung ini,” isteri Budi kembali memiringkan tubuh ke kiri dan menatap Budi. “Kakeknya ketua RT, ayahnya ketua RT, dan sekarang ia pun ketua RT. Memang ada pemilihan ketua RT, tapi itu formalitas belaka. Karena ini kampung kerajaan. Perlu kau tahu, sejak muda ia sudah gemar mencuri!”
“Kau yakin?”
“Ayah yang cerita. Ayah tidak memilihnya ketika pemilihan ketua RT tiga tahun silam. Ayah tidak mau kampung ini dipimpin maling.”
“Dan kau memilih siapa, saat itu?”
“Tiga tahun yang lalu aku baru lulus SMA, belum punya KTP, sayaaaangg!” isteri Budi mencomel dagu Budi. Gemas.
“Baiklah,” kata Budi. “Biar kusimpulkan pembicaraan ini. Ini kampung keraajaan dan ia menjadi menjadi ketua RT karena trah. Lima rumah di selatan jalan, sudah empat rumah yang kemalingan. Hanya rumah kita yang masih aman. Apa menurutmu rumah kita juga akan kemalingan? Menurutmu begitu, rumah kita akan kemalingan juga?”
Tak ada jawaban. Budi menoleh. Mata isterinya terpejam, napasnya naik turun teratur.
***
Tengah malam Budi terjaga. Kamar gelap dan Budi meraba meja kecil di dekat ranjang, tetapi ia tidak menemukan ponselnya, sehingga ia tidak tahu pukul berapa sekarang. Budi beranjak dari ranjang, menekan saklar di dinding dekat ranjang. Lampu menyala dan ia tidak melihat ponselnya di kamar.
Budi keluar kamar dan sekarang ia berada di ruang tengah. Menyalakan lampu ruang tengah. Mencari-cari ponsel di bagian bawah rak televisi, di bagian bawah meja depan televisi, tetapi ponsel itu pun tak ada.
Ah, pasti di dapur. Budi ingat, saat makan malam bersama isteri di dapur, ia sambil membalas email dari bosnya. Budi yakin seribu persen, ponselnya pasti di meja makan di ruang dapur. Seribu email mungkin sudah masuk ke ponselnya.
Budi hendak menuju dapur, namun langkahnya terhenti. Ia mendengar sesuatu dari arah dapur. Berjingkat ia melangkah dan tangannya meraba dinding. Ia menekan saklar dan ketika lampu ruang dapur menyala, Budi terhenyak.
Di sudut ruang dapur, tampak sesosok berpenutup kepala seperti yang biasa dipakai teroris. Sepasang mata sosok itu tampak membelalak dan gerakannya tampak gugup. Ia berusaha lari namun kakinya membentur kaki meja dan ia tersungkur di lantai keramik.
Budi sigap melompat dan menyergap sosok itu. Menelikung tangan sosok itu. Budi merenggut penutup kepala sosok itu dan ia kembali terhenyak.
“Ya, Tuhan! Mengapa njenengan melakukan ini?” seru Budi dengan suara ditekan rendah.
“Ampun, Pak Budi. Ampuni saya,” sosok itu seorang lelaki setengah baya, merintih dengan suara ditekan rendah pula.
“Apa yang njenengan ambil dari rumah saya?”
“Di saku celana saya.”
Budi merogoh saku celana pendek lelaki itu dan ia mendapatkan Samsung Galaxy S6 yang ia cari.
“Mengapa njenengan lakukan ini?”
Budi melepaskan telikungan tangan lelaki itu dan memintanya berdiri. Wajah lelaki setengah baya itu pucat dan matanya tampak resah dan memerah. Mungkin sebentar lagi ia menangis.
Lelaki itu bersimpuh di depan Budi.
“Ampuni saya, Pak Budi. Saya terpaksa melakukan ini demi anak perempuan saya. Saya ingin pernikahan anak saya meriah.”
“Saya bisa melaporkan njenengan ke polisi.”
Lelaki itu memeluk kaki Budi.
“Jangan, Pak Budi. Saya janji, ini yang terakhir.”
“Kalau njenengan ingkar?”
Lelaki itu tertegun.
“Saya janji, Pak. Ini benar-benar yang terakhir.”
“Kalau njenengan ingkar, saya akan laporkan njenengan ke polisi.”
Lelaki itu mempererat pelukan di kaki Budi.
“Ampuni saya, Pak Budi. Saya benar-benar menyesal.”
“Menyesal karena tertangkap?”
“Saya menyesal, Pak Budi. Saya menyesal, saya tobat.”
Budi meminta lelaki itu berdiri dan ia melihat wajah lelaki itu basah oleh air mata. Tak tahan Budi menatapnya dan ia merasakan sepasang matanya menghangat. Mungkin sebentar lagi ia ikut pula menangis.
“Pergilah,” kata Budi. “Tapi ingat, kalau ada pencurian lagi di kampung ini, saya akan laporkan njenengan ke polisi.”
Lelaki itu mencium tangan Budi.
“Terima kasih, Pak Budi. Terima kasih.”
Setelah lelaki itu pergi melalui pintu belakang, Budi kembali ke kamar. Isterinya masih terlelap. Budi mematikan lampu kamar dan pelan-pelan membaringkan tubuhnya ke ranjang besi.
Ranjang besi berderit sesaat.
“Mas bicara dengan siapa? Mas mengigau lagi, ya?”
“Ya, Dik. Mas mengigau.”
Oleh: Sulistiyo Suparno
Cerpenis kelahiran Batang, 9 Mei 1974. Cerpen-cerpennya tersiar di berbagai media. Bergiat di Komunitas Pena, perkumpulan penulis di Batang. Bermukim di Limpung, Batang, Jawa Tengah.