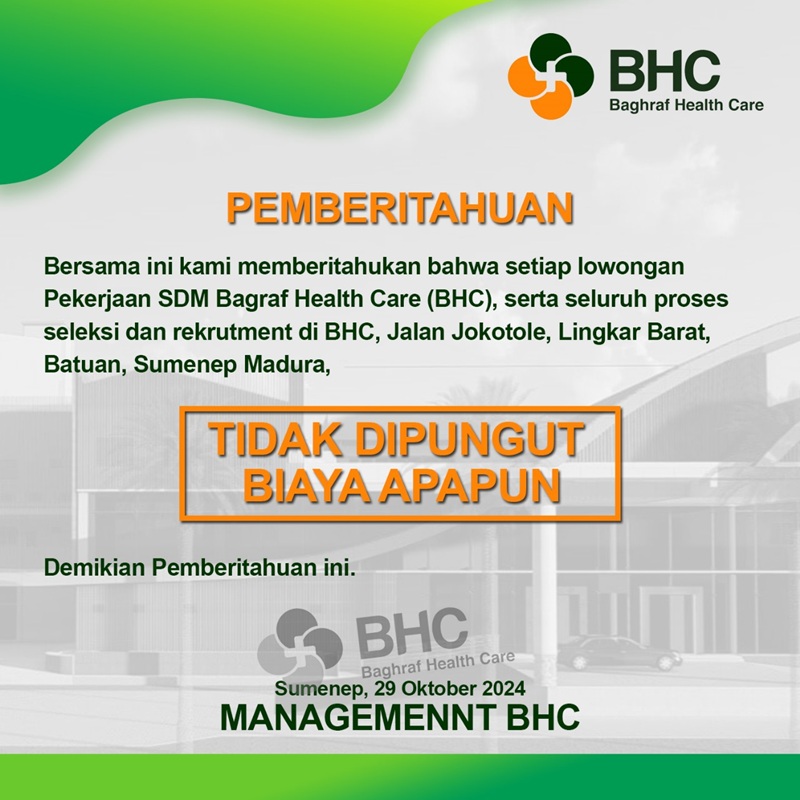Oleh : Adam Setiawan
Dunia permusikan belakangan ini telah digemparkan oleh isu terkait draf RUU tentang Permusikan yang substansinya telah menimbulkan pro dan kontra di antara pelaku industri musik.
Seperti yang diketahui bahwa perjalanan panjang RUU tentang Permusikan dimulai sejak 30 Maret 2015 dimana Komisi X DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan perwakilan dari industri musik. RDPU tersebut membahas kegelisahan para pemangku kepentingan industri musik tentang implementasi UU Nomor 28 Tahun 2014, tentang hak cipta yang belum memihak keberlangsungan industri musik.
Selanjutnya pada 12 April 2017 Anggota Komisi X DPR RI, Anang Hermansyah, menyerahkan Naskah Akademik RUU tentang Permusikan kepada Pimpinan Komisi X DPR RI.
Hingga pada akhirnya 24 Oktober 2018 RUU tentang Permusikan secara resmi masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2019 DPR RI.
Berdasarkan hasil rapat antara Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Dewan Perwakilan Daerah, dan Pemerintah. Total sebanyak 54 pasal ada di dalam draf RUU Permusikan yang disusun oleh Badan Keahlian DPR RI.
Di antara 54 Pasal yang ada di dalam draf RUU tentang Permusikan ada beberapa pasal yang menimbulkan polemik salah satunya adalah Pasal 5 dalam melakukan proses kreasi setiap orang dilarang : a. mendorong khalayak umum melakukan kekerasan dan perjudian serta penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; b. memuat konten pornografi, kekerasan seksual, dan eksploitasi anak; c. memprovokasi terjadinya pertentangan antar kelompok, antarsuku, antar ras, dan/atau antar golongan; d. menistakan, melecehkan, dan/atau menodai nilai agama; e. mendorong khalayak umum melakukan tindakan melawan hukum; f. membawa pengaruh negatif budaya asing; dan/atau g. merendahkan harkat dan martabat manusia.
Selanjutnya berdasarkan Pasal 50 Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Proses Kreasi yang setiap orang dilarang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 akan dikenakan pidana penjara.
Berdasarkan redaksi pasal tersebut, penulis mencoba mengulasnya secara mendalam. Ada beberapa hal yang perlu dicermati dalam melakukan konstruksi substansi dalam undang-undang terkait kekuatan berlakunya undang-undang tersebut dengan beberapa landasaan yakni: a. landasan yuridis b. Landasan sosiologis c. Landasan filosofis.
Pertama, landasan yuridis: undang-undang mempunyai kekuatan berlaku apabila persyaratan formal terbentuknya undang-undang itu telah terpenuhi. Selain itu salah seorang pencetus positivistik Hans Kelsen mengatakan bahwa kaedah hukum mempunyai kekuatan berlaku apabila penetapannya didasarkan atas kaedah yang lebih tinggi tingkatannya.
Sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, RUU tentang Permusikan merupakan upaya negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 32 ayat (1) UUD.
Namun ada hal yang perlu dikritisi terkait substansi Pasal 5 RUU tentang Permusikan. Dalam hal ini menurut penulis pasal tersebut cenderung membatasi ruang gerak pelaku musik untuk berkreasi. Dengan kata lain telah memasung kemajuan kreatifitas para pelaku industri musik. Seperti Pelaku musik dapat saja dikatakan melanggar pasal tersebut apabila bersentuhan dengan kepentingan elit misalnya membuat lagu yang isinya kritik terhadap pemerintah. Sehingga menurut penulis telah memasung kreativitas pelaku industri musik.
Di samping itu menurut penulis ada beberapa point dalam pasal 5 tersebut telah bertentangan dengan Pasal 28 Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
Kedua, landasan sosiologis: bahwa berlakunya atau diterimanya hukum (undang-undang) di dalam masyarakat itu lepas dari kenyataan apakah peraturan hukum itu terbentuk menurut persyaratan formal atau tidak. Ada dua teori dalam melihat berlakunya hukum di dalam masyarakat yaitu teori kekuatan (Machtstheorie) dan teori pengakuan (Anerkennungstheorie).
Secara teori kekuatan (Machtstheorie) hukum mempunyai kekuatan berlaku sosiologis apabila dipaksakan berlakunya oleh penguasa terlepas dari diterima ataupun tidak oleh masyarakat. Sedangkan teori pengakuan (Anerkennungstheorie) hukum mempunyai kekuatan berlaku sosiologis apabila diterima dan diakui oleh warga masyarakat.
Dari kedua teori tersebut, tentunya teori kekuatan (Machtstheorie) tidak dapat dipraktikan di negara Republik Indonesia dengan alasan hukum bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat (3) UUD yang mempunyai esensi negara yang berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Dalam hal ini segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Oleh karena itu teori pengakuan (Anerkennungstheorie) dirasakan sangat relevan jika dihubungkan dengan dapat berlakunya RUU tentang Permusikan, sebagaimana kita ketahui banyak kalangan pelaku musik yang tergabung dalam Koalisi Nasional secara tegas menolak RUU Permusikan. Dengan kata lain dapat diasumsikan bahwa RUU tentang Permusikan tidak dapat berlaku akibat banyak pelaku industri musik yang menolak.
Ketiga, Landasan filosofis: hukum (undang-undang) mempunyai kekuatan berlaku filosofis apabila kaedah hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum (Rechtsidee) sebagai nilai positif yang tertinggi (nilai-nilai Pancasila). Dalam konteks RUU tentang Permusikan menurut penulis bahwa RUU tentang Permusikan yang membatasi kreatifvitas pelaku industri musik sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa Pasal 5 RUU tentang Permusikan bertentangan dengan Pasal 28 Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Dengan demikian dapat dikatakan RUU Permusikan tidak mencerminkan nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila khususnya nilai keadilan sosial. Wujud keadilan sosial yang dimaksud mencakup seluruh aspek kehidupan, tidak hanya ekonomi, namun juga politik dan kebudayaan.
Berdasarkan uraian di atas, dapat disepakati bahwa hukum (undang-undang) dapat berfungsi di antaranya dengan berlandaskan yuridis, sosiologis, dan filosofis secara simultan.
(Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia asal Samarinda)