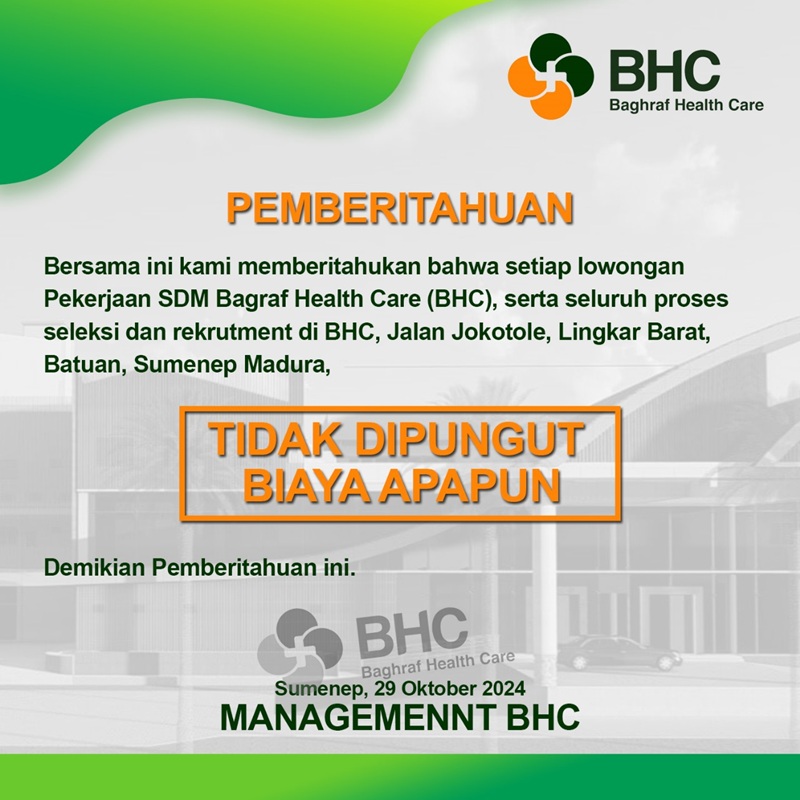KORANMADURA.com – Unjuk rasa mahasiswa masih terjadi di sejumlah daerah di tanah air. Unjuk rasa telah berlangsung sejak 23 September 2019 lalu, dipicu rencana pengesahan sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) dan revisi UU.
Tuntutan para mahasiswa Jakarta relatif sama dengan Aliansi Rakyat Bergerak Yogyakarta, yakni menolak rencana pengesahan RKUHP, UU KPK hasil revisi, dan rancangan serta revisi UU lainnya lantaran dinilai mencederai demokrasi.
Di beberapa daerah, aksi protes itu justru berujung bentrok antara pengunjuk rasa dengan aparat keamanan, bahkan ada yang menimbulkan korban jiwa. Belakangan, aksi juga diikuti kelompok pelajar, tanpa diketahui apakah mereka paham dengan isu yang mereka usung atau sekedar latah dengan apa yang dilakukan para mahasiswa.
Beberapa pihak, menilai aksi serentak itu mengingatkan pada sejarah aksi mahasiswa yang berujung pada “pergantian” kekuasaan, meski ada pihak lain yang meyakini aksi kali ini tidak berpengaruh pada kekuasaan.
Berikut catatan koranmadura.com tentang beberapa aksi mahasiswa yang berimbas pada pergantian kekuasaan.
Pada 1966 terjadi aksi unjuk rasa yang dikenal dengan Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura). Aksi ini merupakan aksi serentak dan massif dilakukan di beberapa daerah dengan isu tunggal “Tiga Tuntutan Rakyat” atau dikenal dengan istilah Tritura. Aksi ini dipicu kondisi ekonomi nasional Indonesia akibat konflik Indonesia dengan Malaysia serta konflik Irian Barat.
Kekacauan politik sebagai imbas sari Gerakan 30 September 1965 (G 30 S) PKI menjadi pemicu utama ditambah kenaikan harga pokok yang mencapai 300 persen. Kondisi tersebut menjadi isu pemersatu antar kelompok gerakan pada saat itu hingga menimbulkan gelombang aksi unjuk rasa di beberapa daerah sentral di Indonesia, seperti Yogyakarta, Jakarta dan beberapa daerah lain di luar Jawa.
Beberapa kelompok pergerakan yang tercatat dalam sejarah terlibat aksi Tritura ini di antaranya Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI), Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI), Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI), serta beberapa kelompok pergerakan lainnya.
Unjuk rasa yang puncaknya terjadi pada 12 Januari 1966 di Gedung Sekretariat Negara tersebut, seluruh elemen yang terlibat, konsisten mengawal tiga tuntutan yang disepakati, antara lain, pembubaran PKI dan ormasnya, penghapusan Dwi Komando Rakyat (Dwikora) dan penurunan harga bahan pokok.
Yang penting menjadi catatan, saat itu tidak ada satupun kelompok pergerakan yang membawa isu berbeda apalagi isu yang berseberangan.
Dari tiga tuntutan itu, pemerintah hanya memenuhi tuntutan pembubaran Kabinet Dwikora dengan alasan dua tuntutan lainnya masih membutuhkan waktu untuk mengkaji.
Kondisi tersebut menyulut aksi lanjutan dengan tuntutan agar Presiden Soekarno mengundurkan diri dari jabatannya karena dianggap tidak mempu mengatasi masalah negara.
Pada 24 Februari 1966, terjadi bentrok antara pengunjuk rasa dengan pasukan Cakrabhirawa yang saat itu berfungsi sebagai pasukan pengaman presiden dan menewaskan seorang mahasiswa, Arif Rahman Hakim. Aksi unjuk rasa terus berlangsung hingga menimbulkan rasa tidak percaya masyarakat pada pemerintahan kala itu. Ujungnya, pada 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) yang menjadi tonggak berakhirnya rezim Soekarno.
Sejarah kedua, terjadi pada Mei 1998 lalu. Aksi mahasiswa berhasil mengakhiri kekuasaan Orde Baru dan mengganti dengan Reformasi.
Seperti yang terjadi pada 1966, aksi ini juga dipicu oleh krisis ekonomi yang terjadi pada 1997, dimana terjadi lonjakan harga bahan pokok akibat anjloknya nilai rupiah hingga ke titik paling rendah saat itu. Mahasiswa memprotes ketidakmampuan pemerintah menangani krisis.
Diawali oleh unjuk rasa di sejumlah daerah, seperti Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Malang, Makassar, para mahasiwa menyatukan isu menjadi tiga isu utama, antara lain reformasi birokrasi, reformasi konstitusi dan penghapusan dwifungsi ABRI.
Bersamaan dengan penetapan kembali Soeharto sebagai Presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pimpinan Harmoko, mahasiswa makin mengencarkan aksi unjuk rasa mereka. Aksi mahasiswa saat itu, tidak hanya berhadapan dengan barikade petugas kepolisian, namun juga berhadapan dengan aparat TNI.
Pemerintah juga mulai melakukan tekanan di antaranya menangkap aktivis, membredel media massa yang dianggap tidak pro pemerintah dan melarang kegiatan-kegiatan yang dianggap mengancam stabilitas nasional.
Namun, justru perlawanan para mahasiswa makin gencar. Apalagi setelah mereka mendapat dukungan dari kalangan lain di luar mahasiswa, seperti akademisi, politisi, seniman dan tokoh masyarakat.
Saat itu mulai tumbuh gerakan perlawanan dengan terbentuknya organisasi di luar pemerintah, seperti Partai Rakyat Demokratik atau PRD, Aliansi Jurnalis Independen, Komite Independen Pemantau Pemilu, dan lainnya.
Pada 12 Mei, terjadi bentrok antara mahasiswa dengan pasukan TNI dan Polri yang berujung pada tewasnya empat mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta yang menyulut terjadinya kerusuhan di hampir seluruh wilayah Jakarta.
Dilanjutkan pada aksi pendudukan gedung DPR/MPR oleh ribuan mahasiswa dari berbagai daerah di tanah air dengan satu tuntutan, yakni Sidang Istimewa MPR dengan agenda penurunan Soeharto dari jabatannya sebagau Presiden.
Lalu pada 21 Mei 1998, Soeharto menyatakan mundur dari jabatan Presiden dan menyerahkan pada wakilnya saat itu, Habibie.
Mantan aktivis ’98, Abu Hanifah, mengatakan ada perbedaan pola dan isu antara aksi mahasiswa saat ini dengan aksi yang terjadi pada 1966 dan 1998 sehingga diyakini aksi serentak kali ini tidak berpengaruh pada kepemimpinan nasional. Saat ini pola unjuk rasa yang dilakukan tidak terstruktur. Masing-masing kelompok terkesan bergerak sendiri-sendiri dan tidak terkoordinasi.
Berbeda dengan yang terjadi pada unjuk rasa 1966 dan 1998. Saat itu, jaringan gerakan mahasiswa cukup kuat, diawali dari jaringan kota hingga jaringan nasional.
“Sudah terbentuk satu jaringan gerakan yang cukup kuat, sehingga isu yang dirumuskan menjadi seragam,” kata Abu Hanifah, dalam diskusi “Merawat Keragaman Indonesia” di Yayasan Sehati, Surabaya, Selasa malam, 25 September 2019.
Peneliti salah satu lembaga survei nasional tersebut menjelaskan selain pola yang berbeda, kondisi yang melatarbelakangi munculnya aksi unjuk rasa juga berbeda. Pada 1998, terjadi akumulasi kejenuhan pada kondisi politik dan kepemimpinan nasional saat itu.
Diawali dengan isu gerakan golput pada 1997, akibat sistem pemilihan umum (pemilu) yang dianggap tidak mengakomodir hak politik dengan baik, isu kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) menjadi isu pemersatu hampir seluruh kelompok perlawanan yang saat itu mulai membangun gerakan bawah tanah.
Maka saat itu muncul beberapa kelompok pergerakan seperti Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI), Front Aksi Mahasiswa Indonesia (FAMI) dan beberapa kelompok lainnya yang menjadi wadah gerakan di luar organisasi kemahasiswaan yang oleh penguasa saat itu diberi label Organisasi Tanpa Bentuk (OTB).
Gerakan bawah tanah itu, merembet ke sektor lainnya, termasuk ke kelompok seniman, jurnalis, kelompok perempuan hingga akademisi.
Tokoh yang bersuara lantang melawan penguasa saat itu, jelas dia, secara otomatis menjadi tokoh sentral gerakan reformasi. Jaringan para tokoh itu, membangun kelompok gerakan yang secara tidak langsung antar kelompok tersebut terbangun jaringan karena adanya kesamaan kepentingan.
“Sebut saja Megawati Soekarno Puteri, Sri Bintang Pamungkas, Amin Rais, Widji Tukul, Gunawan Muhammad, Mulyana W Kusumah, Abdurrahman Wahid dan lain-lain. Saat ini, tokoh sentral seperti mereka tidak muncul karena masing-masing kelompok mengusung kepentingannya sendiri-sendiri,” jelas Abu. (G. MUJTABA/ROS/DIK)