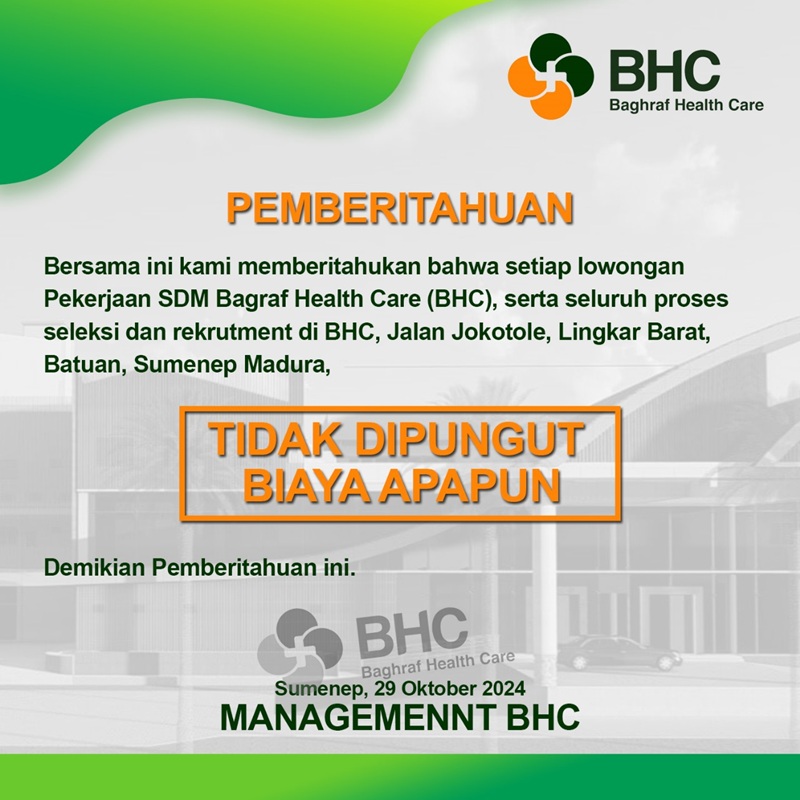Oleh: Miqdad Husein (*)
Di era Orde Baru, sekitar tahun 90 an, sekali waktu seorang Panglima Kodim mendatangi Ketua Majelis Ulama Indonesia Cirebon, Habib Saleh Assegaf. Sang Panglima bersilaturrahmi antara lain mempertanyakan aktivitas pengajian relatif besar, yang diprakarsai H. Yukeng yang biasanya diselenggarakan malam Sabtu, di sekitar kawasan Gunang Sari, Cirebon.
Pengajian rutin di kediaman H. Yukeng memang tergolong spektakuler masa itu. Penceramah kondang seperti KH. Zainuddin MZ, KH. Sukron Ma’mun, KH. Soemarno Syafi’i tampil rutin. Termasuk beberapa da’ i lokal sekitar Wilayah III Cirebon. Aktivitas itu, rupanya -khas pandangan rezim Orde Baru- dianggap perlu mendapat perhatian sehingga mendorong sang Panglima datang bersilaturrahmi kepada Ketua MUI.
Habib Saleh Assegaf tidak menjawab langsung namun justru justru balik bertanya. “Kenapa dengan Yukeng? Apa masalahnya? Bukankah dia hanya menyelenggarakan pengajian,” katanya.
Bapak harusnya bersyukur, lanjut Saleh Asseggaf lagi. “Ketika masyarakat Tionghoa lain terkesan tidak bisa berbaur, H. Yukeng justru mampu menyatu dengan masyarakat lingkungan sosialnya. Bersama-sama umat Islam Indonesia, khususnya masyarakat Islam Cirebon. Bukankah itu sangat bagus dan sesuai harapan pemerintah,” katanya.
Panglima terhenyak mendapat penjelasan Saleh Assegaf. Dia, seperti diceritakan Saleh Assegaf seakan disegarkan informasinya sehingga kemudian sepenuhnya memahami dan mengerti.
Melalui dialog itu, Saleh Assegaf seperti ingin menegaskan tentang kesetaraan, kesamaan manusia berdasarkan ajaran Islam. Dengan berislam batas-batas suku, etnis, golongan mencair. Manusia sama kedudukannya. Bahkan secara sosial dalam bidang hukum misalnya perbedaan agama dalam pandangan Islam tidak membuka ruang perlakuan khusus. Semua diperlakukan secara adil.
Pertanyaan Panglima, yang menghawatirkan kegiatan H. Yukeng, di masa itu memang bukan hal luar biasa. H. Yukeng, yang Tionghoa, kegiatan keislaman pengajian yang ‘membludak’ jelas mengundang perhatian kekuasaan. Kondisi kekuasaan otoritarian saat itu, membuat segala sesuatu dicurigai dan dikhawatirkan. Masalah SARA yang selalu jadi kewaspadaan rezim Orba sekaligus juga melalui perspektif bernuansa SARAlah cara memandang pelbagai persoalan sosial.
Era reformasi, terutama belakangan ini, ketika kebebasan dibuka, demokrasi dikembalikan secara proporsional, ketika warga dapat leluasa mengekspresikan hak-haknya, ironisnya merebak kembali kecenderungan segelintir masyarakat memantik sikap rasialis. Bukan dari pemerintah tentu saja, tapi dari segelintir masyarakat.
Perbedaan suku, keturunan, golongan di era digital seperti sekarang, ketika globalisasi makin menjadi keseharian seperti digelar kembali. Identitas Arab, Cina, India, Pakistan, Asing, Aseng seakan kembali dijadikan sekat-sekat sosial. Demikian pula identitas agama, seperti dibentangkan kembali membentuk kelompok-kelompok.
Lihatlah belakangan ini, di media sosial ungkapan sarkastik seperti pendatang Yaman, Aseng, Pakistan dan lainnya disertai berbagai bumbu-bumbu olok-olok bernuansa diskriminatif dan cenderung rasialis bermunculan. Di kalangan mayoritas umat Islam, lebih kental lagi dalam format pengerasan kelompok atas dasar pemahaman. Mereka yang hanya berbeda pemahaman dianggap bukan bagian dari kelompoknya, hingga kadang pada tingkat serius memunculkan sikap saling mengkafirkan.
Bukan hal luar biasa jika Nahdatul Ulama (NU) dalam beberapa tahun belakangan ini, menegaskan tentang perlunya pengembangan Islam Nusantara; sebuah ajakan mengembangkan keislaman yang ramah, yang menghargai perbedaan khas masyarakat Indonesia. Demikian pula Muhammadiyah, yang mengajak masyarakat dalam nada sama dengan jargon Islam Berkemajuan. Baik NU dan Muhammadiyah semuanya berangkat untuk mencairkan pengerasan kelompok, yang merebak hanya karena perbedaan pemahaman keterikatan keagamaan.
Tentu saja, fenomena rasis ini mengherankan, sangat kontradiktif dengan kenyataan sosial. Bukankah digitalisasi berbagai bidang, yang mensyaratkan efisiensi, efektivitas, persaingan ketat atas dasar spesialisasi keahlian sudah menyatukan masyarakat dunia. Siapapun, atas dasar latar belakang sosial apapun, bebas berekspresi. Melalui media sosial, kebebasan luar biasa memberi ruang ekspresi personal tanpa perlu membawa identitas agama, suku, golongan atau apapun.
Di era digital tanpa batas ini, seharusnya tidak ada lagi berbicara tentang latar belakang keturunan apalagi yang telah ratusan tahun berada di negeri ini. Ketika seseorang secara hukum menjadi WNI, bahkan yang melalui proses naturalisasi, mereka memiliki hak dan kewajiban sama. Semua warga memiliki hak sama, perlakuan hukum sama, tanpa kecuali.
Siapapun yang memulai, memperlihatkan cara berpikir mundur ke belakang. Atas dasar dan latar belakang apapun seluruh warga negara di negeri ini memiliki hak dan kewajiban sama. Yang membedakan adalah prestasi, kinerja dan hal obyektif lainnya. (*)
*Kolumnis, tinggal di Jakarta.