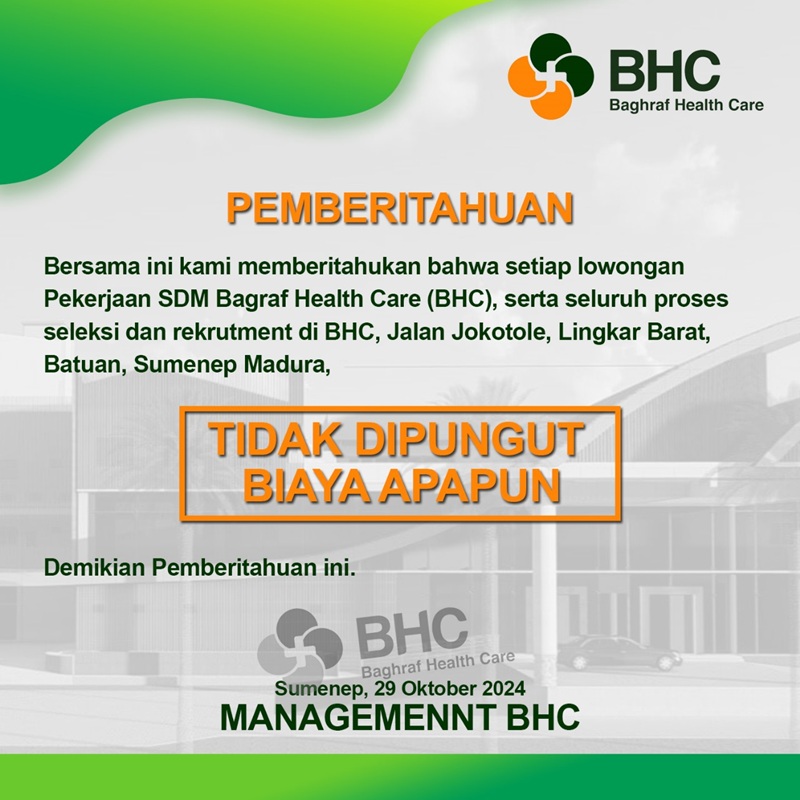Oleh: Ahmad Mahrus Alie (*)
Secara teoritis sumber-sumber kekuasaan yang terbatas akan terus menjadi rebutan, walaupun memerlukan biaya yang mahal, dan dimungkinkan akan memunculkan konflik. Kekuasaan menjadi perhatian utama para elit politik. Untuk “memperebutkannya” seringkali harus menaruhkan segala-galanya. Oleh karena itu untuk menjadi calon kepala daerah mereka rela mengorbankan harta benda yang tidak sedikit jumlahnya. Demikian pula sebaliknya, jika ia masih berkuasa dengan segala cara untuk mempertahankan status quonya.
Dalam konteks pergantian kekuasaan sebagai akibat tuntutan demokrasi dari rezim lama kepada rezim baru, ternyata di beberapa daerah menimbulkan persoalan. Tajamnya perebutan dan kepentingan politik antar kekuatan politik maupun intra kekuatan politik, mengakibatkan konflik yang seringkali tidak terhindarkan dalam perebutan jabatan-jabatan politik. Rivalitas politik, kadang-kadang bukanlah semata-semata sebagai akibat dari perbedaan persepsi, melainkan perbedaan kepentingan antar kekuatan politik dalam memperebutkan sumber-sumber kekuasaan di tingkat lokal.
Selain itu, konflik yang terjadi mencerminkan sikap dan perilaku politik kekuatan politik lokal yang relatif masih “belum matang “. Hal ini dicerminkan belum “bakunya” insfrastruktur pemilihan pejabat publik yang seringkali kontroversial, dipersoalkan oleh partai politik dan aktor politik serta kadang-kadang ditolak oleh masyarakat, bahkan oleh partai politik maupun anggota legislatif yang partainya kalah dalam pemilihan jabatan politik lokal.
Kesempatan yang ada menggiring suasana politik dan kiai dapat terdorong untuk ‘mengarahkan’ para pemilih kepada pihak salah satu partai politik tertentu, bahkan kemungkinan besar partai yang didukung oleh para kiai menjadi partai terbesar dalam pemilu. Karena itu, keberadaan kiai menjadi sangat penting dalam kehidupan politik yang sedang dibangun bangsa ini. Ada beberapa hal spesifik dari kiai yang ada dalam masyarakat kita, selain ada kiai sepuh dan sebangsanya, yaitu mereka yang menjadi pengasuh pesantren- pesantren besar. Mereka menjadi pihak yang tidak lagi mampu berkomunikasi langsung dengan rakyat, karena para pengasuhnya adalah kiai-kiai yang bergaul dalam bahasa pesantren ‘disowani’, oleh kiai-kiai yang ‘kelasnya’ ada di bawah mereka. Jadi, mereka tidak lagi berhubungan langsung dengan rakyat, tetapi dengan para penghubung. Yang menyekat hubungan langsung dengan para penganut itu,dapat saja berupa kiai-kiai pondok pesantren yang kecil, para pejabat pemerintahan ataupun pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan peranan mereka. Bahkan,banyak juga kiai sesepuh yang ‘berkenalan’ dengan uang, kekuasaan dan jabatan. Banyak juga di antara kiai itu yang dihadapkan kepada ‘keharusan’ menghadapi penilaian-penilaian oleh kiai sesepuh tentang keadaan yang dihadapi. Tetapi hal yang kemudian menjadi hal pendorong para kiai untuk melakukan intervensi kepada santri untuk menentukan pilihan politiknya dengan dalih fatwa-fatwa yang disampaikannya sehingga para santri tidak lagi bisa mengelak dari apa yang sudah difatwakan oleh kiainya.
Terkait dengan uraian tersebut diatas, aktor politik yang turut berperan dalam demokrasi dalam hal pemilihan kepala daerah adalah pesantren atau lebih dikenal dengan aktor kiai dan santri, di mana para calon kepala daerah berlomba-lomba mendekatkan dirinya untuk mendapatkan dukungan dari pesantren.
Pesantren sebagai lembaga Islam tradisional tertua di Indonesia juga telah melakukan transformasi. Perubahan telah menyentuh institusi ini. Pesantren yang pada dasarnya merupakan subkultur dalam kehidupan setelah masyarakat, telah bergeser perannya tidak sekedar lembaga yang mencetak kiai atau ulama dan intelektual muslim yang diharapkan dapat melanjutkan cita-cita para pendahulunya untuk memajukan umat Islam secara keseluruhan.
Perubahan dimaksud salah satunya dapat kita lihat dari pola hubungan kiai-santri yang pada awalnya kita kenal bersifat patron-client yang mengandaikan pola hubungan guru-murid. Sebagai guru, kiai tidak hanya dikenal sebagai sosok yang mumpuni dalam ilmu pengetahuan agamanya serta memiliki akhlakul karimah, namun pada sisi yang lain kiai juga mempunyai pengaruh yang sangat luas di dalam masyarakat melalui kharisma yang mereka miliki. Tak pelak, kiai merupakan figur dambaan umat dan senantiasa mendapat tempat yang mulia dan tinggi dalam struktur masyarakat. Hal tersebut menarik diperhatikan, sebab saat ini untuk menuju Istana Negara pun, seorang calon presiden dalam dua kali Pemilu terakhir, selalu “menggunakan” pesantren, kiai dan santri untuk mendapatkan legitimasi dan dulangan suara. Dalam hal ini, tokoh agama, termasuk agama Katolik, Kristen, Hindu, Buda dan lainnya, adalah magnet politik yang sangat kuat. Ada beberapa alasan yang mendasari tindakan komunitas pesantren untuk terus berada dalam pusaran politik. Pertama, sebagai lembaga yang mengabdikan kepentingannya untuk melayanani masyarakat, kalangan pesantren merasa mendapat kewajiban (fardlu ain) menyampaikan aspirasi umat kepada penguasa (umara). Terlebih ada ungkapan yang mengumpamakan sulitnya menegakkan aspirasi tanpa kekuasaan. Tingkat kesulitan itu bahkan digambarkan bagai menegakkan benang basah. Kedua, sebagian ulama ada yang merasa harus melakukan tugas amar makruf nahi munkar (menyerukan kebaikan dan mencegah kemungkaran) yang hanya efektif dilakukan melalui jalur kekuasaaan. Alasan yang bersifat teologis itu menganggap politik bisa dijadikan sebagai salah satu alat perjuangan dan mempermudah dakwah mereka. Ini yang yang cendrung menjadi alasan bagi para kiai politik untuk memudahkan kapentingan politik dangan kekuatan legitimasi pondok pesantrennya yang memudahkan untuk mewujudkan semua keinginan politiknya, Bahkan bagi mereka partai politik adalah alat perjuangan yang berlandaskan kepentingan umum (mashlahah al-’ammah), bukan kepentingan kelompok, apalagi pribadi. Tidak mengherankan, saat ini kiai tidak hanya sebagai supporter penguasa, bahkan tidak sedikit yang terjun langsung sebagai penguasa eksekutif maupun legislatif.
Santri merupakan elemen dalam tradisi pesantren yang kedudukannya lebih rendah dari kiai. Sebagai pengikut, santri harus senantiasa taat, tawadu dan hormat kepada gurunya. Santri dalam kehidupan sehari-harinya harus senantiasa mengikuti apa yang dititahkan oleh seorang kiai. Hal yang sangat strategis untuk mengantarkan para elit politik yang mempunyai kepentingan untuk memuluskan menjadi penguasa di legislatif ataupun di eksekutif. Mengapa santri harus tunduk dan patuh pada kiai? Hal ini didasarkan atas asumsi bahwa kiai merupakan sumber ilmu pengetahuan di pesantren dan penjaga moral santri, sehingga tidak patuh terhadap kiai berarti mereka telah merusak tradisi pesantren yang telah dibangun ratusan tahun lamanya, dan hal ini akan dianggap sesuatu yang tidak wajar. Keberadaan kiai tentu saja sangat sentral dalam konteks perpolitikan di negeri ini. Sebab, sejauh apa pun pandangan seorang santri, mereka selalu masih mencari referensi kepada guru atau kiainya. Kalau dahulu pengamat menyebut kiai hanya sebagai cultural broker, kini peran itu meluas dan mendalam sebagai agency dan pencipta trend, patron politik dan pemutus tunggal. Tidak hanya keputusan keagamaan, bahkan keputusan politik juga diserahkan kepada kiai. Mengapa masyarakat memberikan mandat bahkan nyaris berupa monopoli kepada kiai sedemikian rupa? Menurut sejumlah kajian, sikap tersebut merupakan bentuk kepatuhan yang didasari landasan pikiran keagamaan. Dalam konteks sejarah, kiai terbukti selalu menjadi pemimpin dan penyelesai perkara rakyat. Sementara itu, konteks tersebut juga diperkuat dengan justifikasi bahwa al-Ulama warastatul anbiyak atau Kiai adalah penerus nabi yang harus didengar titahnya dan diikuti sikapnya. Oleh karena itu, pilihannya adalah mendengarkan dan mentaati (sami’na wa atha’na). Dalam keadaan seperti inilah, seorang kiai dengan pesantren dan santrinya menjadi sangat penting di mata penguasa. Demikianlah, kiai memang magnet penyedot dalam pusaran kekuasaan. Tidak peduli penjajah seperti Belanda dan Jepang, para penguasa pribumi juga cenderung menjadikan kiai sebagai patner untuk tujuan kemaslahatan sepihak mereka. Misalnya, Habib Ustman al-Shahab pada abad ke-19, seorang ulama Betawi yang selalu dimintai bantuan nasihat oleh Belanda. Van der Plas (Gubernur Hindia Belanda Jawa Timur), A.H. Ono (pembesar Jepang) yang merasa perlu melakukan perjalanan keliling pesantren pada saat sedang menduduk jabatan tinggi di Jatim. Para penguasa menyadari kedahsyatan kiai dan kiai tidak berdaya mentas dari pusaran politik itu. Akhirnya, pilihan yang dapat diambil manfaatnya adalah berperan dan mewarnai kekuasaan seperti banyak kita saksikan saat ini. (*)
*IKA PMII Kabupaten Sampang.